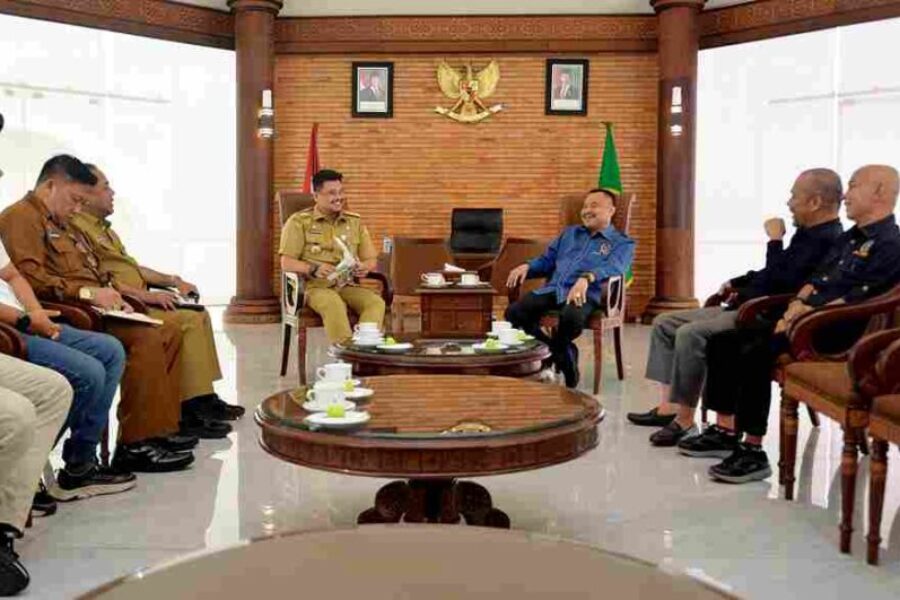Pers Terjebak: Kepentingan Politik, Uang, dan Runtuhnya Independensi
Solusi Berita
KARAWANG | Kondisi media di Indonesia saat ini berada pada fase paling rapuh sejak era Reformasi. Kemerosotan kepercayaan publik terhadap media, yang juga melanda berbagai negara lain, tak lepas dari upaya sistematis untuk melemahkan legitimasi pers, maraknya disinformasi yang disebarkan elite politik, serta narasi yang menempatkan media sebagai pihak yang seolah-olah berseberangan dengan kepentingan publik. Hirst (2022) dalam Journalism Ethics at the Crossroads menyebutkan bahwa paradigma lama praktik jurnalistik dianggap tak lagi memadai, karena gagal merespons krisis besar seperti pandemi COVID-19, konflik rasial, hingga disinformasi politik dengan cara yang etis dan berimbang. Gambaran tersebut tercermin jelas di lanskap media Indonesia. Di tengah polarisasi politik dan tekanan ekonomi, banyak redaksi kehilangan daya kritisnya. Ketika media arus utama mencoba mengkritisi pemerintah, mereka justru dilabeli sebagai partisan atau anti-pemerintah.
Dalam situasi ini, etika jurnalistik tidak hanya ditentukan oleh kode etik profesi, tetapi juga oleh siapa yang mendanai redaksi dan menggaji jurnalis. Media yang terlalu dekat dengan kekuasaan pun kehilangan legitimasi di mata publik karena dianggap tak lagi independen. Perpaduan tekanan finansial dan kaburnya batas antara kepentingan bisnis dan politik turut menggerus kredibilitas redaksi. Hal ini semakin diperparah oleh dominasi media sosial yang kini menjadi sumber informasi utama publik. Media tak hanya bersaing dengan sesamanya, tapi juga melawan algoritma platform digital yang menawarkan kecepatan, sensasi, dan konten personal. Akibatnya, peran media sebagai penjaga kepentingan publik tergerus, sementara media sering hanya mampu mengimbau “jangan percaya hoaks” tanpa menyediakan alternatif konten yang lebih mendalam dan relevan.
Tekanan ekonomi, disrupsi digital, dan ketergantungan pada belanja iklan pemerintah memaksa banyak perusahaan media untuk memilih: menjaga idealisme editorial atau bertahan secara komersial. Di antara dilema itu, yang paling terpuruk adalah para pekerja medianya sendiri—jurnalis, editor, dan kru produksi—yang kini masuk dalam kategori “precariat,” yakni pekerja tanpa kepastian kontrak, jaminan sosial, dan masa depan yang jelas.
Pada periode 2023–2024, PHK massal melanda industri media Indonesia. Dewan Pers mencatat sekitar 1.200 pekerja media kehilangan pekerjaan. Penyebab utamanya adalah penurunan tajam pendapatan iklan media lokal, lantaran sekitar 75 persen belanja iklan nasional kini diserap platform digital global seperti Google, Meta, dan TikTok. Beberapa media besar terdampak signifikan: Kompas TV merumahkan sekitar 150 karyawan, CNN Indonesia TV mem-PHK lebih dari 200 orang, TV One merumahkan sekitar 75 pekerja, sementara ANTV dan media lain di bawah grup Emtek memecat sekitar 100 orang. Yang paling drastis, kanal SEA Today yang berada di bawah Telkom Indonesia dan Kementerian BUMN menutup seluruh operasionalnya pada pertengahan 2025.
Dari sisi keuangan, VIVA Group yang menaungi ANTV dan tvOne mencatat kerugian besar dua tahun berturut-turut, dengan kerugian Rp 942,7 miliar pada 2024 dan utang menumpuk hingga Rp 8,79 triliun. Pendapatan turun drastis dan efisiensi internal pun tak mampu membendung beban bunga yang tinggi. Sementara itu, Tempo Inti Media Tbk justru mencatat kinerja keuangan lebih baik: laba bersih naik menjadi Rp 2,18 miliar pada 2024, dengan pendapatan tumbuh ke Rp 253,8 miliar. Tanpa gelombang PHK besar, Tempo tetap menjaga kredibilitas melalui strategi transformasi digital dan konten berkualitas. Kontras ini membuktikan bahwa kepercayaan publik dan manajemen adaptif bisa menjadi modal yang lebih kuat daripada sekadar investasi besar.
Lebih dalam, krisis ini bukan hanya soal neraca rugi-laba, tetapi perubahan struktur kerja media sendiri. Banyak jurnalis yang di-PHK kini bertahan sebagai pekerja lepas atau content creator dengan pendapatan tidak tetap. Survei AJI Jakarta 2024 menyebut hanya 15 persen jurnalis yang menerima gaji sesuai standar layak, sementara 30 persen digaji di bawah Rp 2,5 juta dan mayoritas bekerja tanpa kontrak resmi atau perlindungan sosial. Kondisi ini memperkuat fenomena “precariat” yang dikemukakan Guy Standing, di mana ketidakpastian ekonomi membuat jurnalis lebih memilih memproduksi konten cepat dan dangkal daripada liputan investigasi atau mendalam yang memerlukan waktu dan biaya.
Pada akhirnya, krisis media di Indonesia bukan sekadar soal penurunan iklan atau PHK massal, tetapi tentang merosotnya fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Dan di tengah krisis inilah, publik semakin sulit menemukan media yang benar-benar independen dan kritis. (D/S)